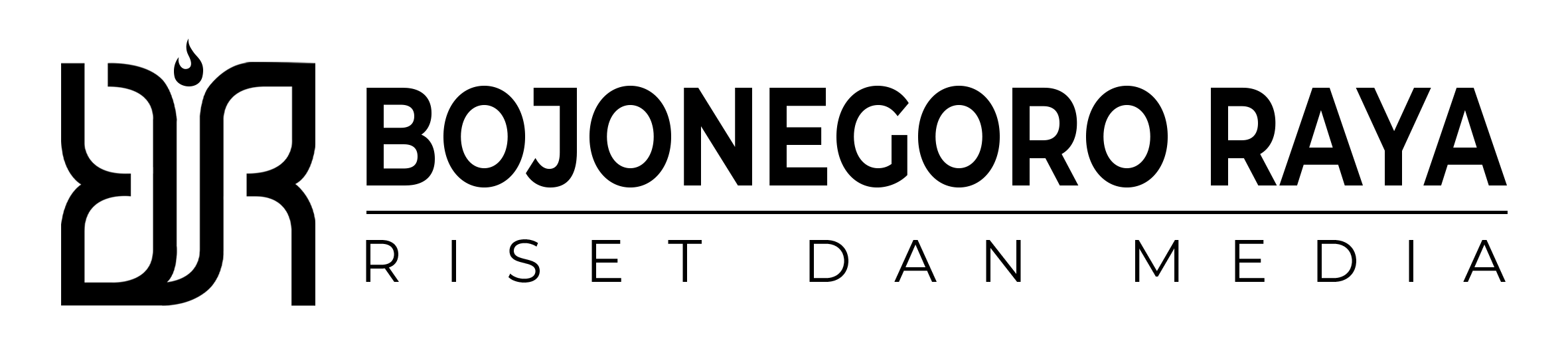SUDAH semingggu, novel yang kubaca luput dari tangan. Aku lupa di mana terakhir meletakkan.
Baru, ketika seorang temanku sedang mabuk bertanya spontan, “He, apa lokalisasi Talisari masih buka sekarang?” maka aku ingat di mana novel itu kutinggalkan.
Sungguh, betapa malu mengingatnya. Namun, harus kukatakan juga. Seminggu lalu, aku memaksa diri kunjungi Talisari. Sebuah lokalisai kebanggan kota kami.
Bukan, aku tidak bermaksud membela diri. Tapi aku punya alasan mengapa aku harus ke sana. Ya, lagi-lagi urusan asmara. Waktu itu aku putus cinta.
Dan, kebisaanku menulis cerpen, puisi, juga opini terputus pula. Sangat tak masuk akal. Tapi memang, hidup ini tak bisa selesai hanya dengan akal.
Singkatnya, aku menuju ke Talisari. Sesampainya dalam kamar yang didominasi cat warna jambon, perbuatan tak senonoh itu terjadilah.
***
“Mas, ibu mengatakan aku ini yang paling cantik dan paling muda. Hanya orang istimewa yang bisa masuk sini,” kata Sinta, perempuan itu.
“Tidak, orang yang kau anggap ibu itu keliru. Aku orang biasa saja. Tapi tak terlalu tua untukmu. Aku dua tiga, engkau barangkali dua puluh,” balasku.
“Tebakanmu hampir benar, Mas, tapi masih keliru. Aku sembilan belas. Dua bulan lagi baru dua puluh,” jawabnya sambil tersenyum kecil.
Tiba-tiba ia bergegas menuruni ranjang. Dengan ringkas, ia berpakaian ala kadar. Rambut sebahu itu ia kuncir satu ke belakang. Dan, ia melangkah ke pojokan. Duduk bersimpuh sangat manis, Sinta meraih tasku dan membuka resletingnya-satu per satu.
“Engkau mencari apa?” tanyaku setelah ia mengorek isi tasku.
“Ibu bilang, engkau sastrawan. Kau pasti membawa buku,” jawabnya tanpa berpaling padaku. Sedang tangannya masih mengorek isi tasku.
Aku menghela nafas, “Buku di bagian paling dalam. Tempat laptop,” terangku.
Sinta kemudian kembali padaku memegang buku, “Sebuah novel,” ia menggumam sendiri.Wajahnya makin berseri. Perlahan ia naik ranjang. Daging muda itu kembali merebahkan diri. Lalu buku terbuka, tepat di depan wajahnya.
“Tidak baik membaca buku dengan posisi seperti itu,” tegurku.
“Lebih tidak baik lagi, jika seseorang tidak membaca, padahal dia dalam posisi sempurna, Mas,” jawab Sinta sambil tersenyum pada buku. Bukan padaku!
“Ibu yang mengajari engkau berkata-kata seperti itu?”
“Tidak. Dari buku saja. Dulu jaman masih sekolah, aku suka ke perpustakaan.”
Aku bangkit dari merebahkan diri. Kata-kata perpustakaan yang keluar dari bibir Sinta membuatku penasaran.
“Apa saja yang kau baca di perpustakaan?”
“Apa saja, Mas,” jawabnya singkat sambil tetap membaca buku. Kurang ajar. Hatiku rasanya ingin bertepuk tangan untuk perempuan ini.
“Engkau betul suka membaca?”
“Betul,” ia menutup buku dan memandangku, “Karena itu, Mas, tinggalkan bukumu di sini. Engkau tak perlu membayar. Biar aku yang jelaskan pada ibu nanti,” lanjut Sinta, kemudian ia membaca buku lagi.
Aku merasakan puas berlebihan melihatnya membaca buku. Maka buku itu tak kupinjamkan padanya, melainkan kuberikan saja. Buku itu baik untuknya-sangat berguna untuk otak dan dagingnya yang masih muda.
***
Ingatan tentang Sinta ini merangsang jiwaku untuk ke Talisari lagi, menyusul temanku yang sedang mabuk tadi. Sekali ini orang boleh menuduhku sedang mabuk pula. Terserah. Aku tak peduli. Dengar, ini bukan alibi, aku hanya ingin memastikan Sinta masih membaca buku ataukah tidak. Itu saja.
Maka, dengan motor bikinan China aku menuju sana. Sudah bertahun-tahun aku tunggangi motor ini. Dan, tak ada yang memprotes, juga diriku sendiri.
Justru, protes datang datang dari motor China ini sendiri. Hampir tiap bulan motor ini mengatakan, “Tuan, oli sudah waktunya diganti. Tuan, kampas remku sudah tipis, dan sebagainya.” Betapa manja motor China ini, geramku kadang-kadang.
Lima belas menit aku sudah sampai di Talisari. Jalanan berubah sangat buruk. Ketika aku mampir membeli rokok di salah satu warung sekitar, si pedagang bilang, “Jalan hancur karena sering dilewati truk berton-ton beratnya, Mas. Baru enam hari lalu, berdiri pabrik cor di dekat sini,” jarinya menunjuk ke arah utara.
“Tiap hari, Mas, bisa tiga puluh truk keluar masuk. Pagi, siang, sore, sampai malam. Gila. Orang bekerja seperti mesin. Tak kenal waktu, tak kenal diri, hanya kenal pada gaji,” imbuh si pedagang.
Aku tak menjawab banyak, hanya mengatakan terima kasih banyak atas informasinya, lalu berlari kecil mencari rumah di mana novel kutinggalkan.
Ketika sudah kutemukan, aku segera masuk halaman dan buru-buru membuka pintu. Suara derit pintu memberi sinyal dan ibu pemilik rumah menyambutku, “Ah, sastrawan kita datang,” katanya sambil tertawa kemudian mengambil duduk.
“Ya, Bu. Sudah lama saya tidak kemari,” aku mengambil duduk di seberangnya. Di antara kami ada meja dengan vas warna jingga berisi sekuntum bunga mawar berbahan plastik.
“Alah, belum lama. Baru seminggu,” balasnya menggoda.
“Sepertinya begitu,” jawabku malu.
Setelah puas menggoda, ia mengeluh padaku, “Setelah bersamamu, anakku jadi lekat dengan buku. Beberapa kali tak mau layani orang karena lebih pilih baca buku. Edan. Entah apa yang dibaca. Sekali waktu, ibu pernah lihat dia membaca sambil menangis. Aneh sekali.”
Aku kaget mendengar keluhan ibu itu. Tapi hatiku puas. Ada pembaca buku di tempat seperti ini—di lokaliasi. Itu sangat membanggakan citra literasi Indonesia!
“Lalu, di mana dia sekarang, Bu? Aku ingin melihatnya,” tanyaku cepat-cepat.
Ibu itu tersenyum, “Bohong kalau kau hanya ingin melihatnya saja,” balasnya.
Keparat. Aku tak ingin ditelanjangi lebih lama lagi oleh ibu ini. Tanpa pikir panjang, uang sisa beli rokok kuberikan semua padanya.
“Dia tetap di kamar yang seminggu lalu. Itu kamarnya sendiri. Dia pasti di sana, barangkali juga sedang membaca buku. Silahkan kau temui,” kata ibu itu sambil tersenyum, setelah memasukkan uang dariku ke dalam dadanya.
***
Sampai di kamar Sinta, aku memerlukan mengintip dari korden yang sedikit terbuka. Betul, dia sedang bersila di atas ranjang, menunduk membaca buku. Rambutnya menutup sebagian wajah. Hatiku bergetar melihat pemandangan itu. Namun aku tak boleh peduli lagi soal perasaan jatuh cinta.
“Sudah baca sampai halaman berapa, Sin?” tanyaku ketika membuka pintu kamarnya.
“Tepat sekali!” ia melompat dari ranjang dan menyeretku masuk kamar,
“Baru saja selesai, Mas. Bagus sekali ceritanya,” ungkapnya.
“Engkau … sampai menangis … ya … ketika membacanya?” kataku terbata-bata karena tubuhku direbahkan olehnya dan oleh hasratku sendiri.
Sinta yang juga sudah rebah menjawab, “Ya, kata-kata penulisnya sangat kuat. Pengungkapan perasaan menderita dan teraniaya detail sekali. Aku sampai merasakan menjadi tokohnya, Mas!” matanya berbinar memandangku.
Lagi-lagi aku ingin bertepuk tangan dalam hati. Engkau perempuan cerdas. Engaku cocok menjadi istriku, atau … maksudku, teman ngobrolku, kataku dalam hati pula.
“Kau punya banyak buku di rumah?” selidiknya.
“Lumayan banyak. Kalau mau, kapan-kapan aku bisa ajak kau ke rumahku.”
“Ah, tidak bisa seperti itu, Mas,” keluhnya, “Tapi engkau bawa buku kan sekarang?”
“Ya, tapi cuma satu judul,” jawabku.
“Kalau begitu mari lakukan, Mas. Setelah itu, aku akan segera membaca buku yang kau bawa itu,” sergahnya.
***
Aku benar-benar tak sempat membalas ajakan Sinta dengan kata-kata. Tanpa irama, jiwa dan dagingnya naik ke atasku dan jiwaku. Aku tenggelam, Sinta membenam. Kami berteriak, mengaduh, dan mengeluh, layaknya para korban dalam film Titanic.
15 November 2024
Yusab Alfa Ziqin
Jurnalis Bojonegoro Raya